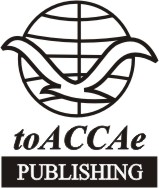Pahlawanku,
Takkan Kulupakan Engkau
Oleh Gina Maliha Rahmawati
Oleh Gina Maliha Rahmawati
Buku ini adalah sebagai pemenang lomba mengarang yang diadakan UNESCO – Ikapi
dan diterbitkan oleh “Pelita Masa” Bandung, pada tahun 1960. Apabila kita
membaca novel ini, terasalah oleh kita suasana yang mempengaruhi Sulawesi
Selatan umumnya kota Palopo.
Novel yang mempunyai alur maju mundur ini berceritakan tentang bagaimana bangsa
Indonesia yang besar sedang diuji. Pemberontakan dimana-mana dan rakyat
menderita. Untuk mencapai cita-cita yang mulia sebagai suatu bangsa yang besar,
bangsa Indonesia, terlebih dahulu harus membayarnya dengan kenyataan yang
pahit. Pada awal tahun 1946 kota palopo, yang sering kita kenal sebagai kota
revolusi ini hancur lumat dicabik-cabik oleh api revolusi kemerdekaan, dibakar
oleh kekejaman para sekutu.
Didalam novel ini pun sudah mulai hilang bahasa-bahasa melayu. Jadi mudah untuk dipahami. Novel ini pun mempunyai sudut pandang sebagai orang ke-3 dan merupakan novel yang mempunyai gambaran tentang masa penjajahan Indonesia sebelum dan sesudah merdeka.
Didalam novel ini pun sudah mulai hilang bahasa-bahasa melayu. Jadi mudah untuk dipahami. Novel ini pun mempunyai sudut pandang sebagai orang ke-3 dan merupakan novel yang mempunyai gambaran tentang masa penjajahan Indonesia sebelum dan sesudah merdeka.
Dalam novel inipun diceritakan kisah hidup seorang guru muda, yaitu ibu Hamida
yang mempunyai semangat besar untuk mengajar anak-anak di Sekolah Rakyat II
Kampung Pisang. Dengan ketulusan hatinya ia mengajarkan kepada anak-anak
pentingnya mangetahui sejarah. Apalagi sejarah negeri kita sendiri. Kita bisa
tahu dan meneladani perjuangan-perjuangan para pahlawan pada zaman revolusi
itu. Bu Hamida pernah mengalami pemeriksaan oleh Sersan Mayor Bambang karena
diduga bersekongkol dengan para gerombolan. Tapi itu semua tidak membuat Ibu
Hamida menyerah untuk mengajar. Menurutnya mengajar adalah hal terpenting dari
hidupnya.
Yang lebih menarik lagi dalam cerita ini digambarkan pergabungan diantara paham
separatisme dengan dendam pribadi, laksana ombak kecil menumpang diatas
gelombang besar. Dan juga menggambarkan betapa besarnya pengaruh ajaran sirik,
yaitu suatu ajaran menjaga nilai harga diri pada suku bangsa Bugis, Makasar,
Mandar, dan Toraja.
Penting sekali buku ini, untuk kita kenang kembali bagaimana suasana, kondisi dan situasi tanah air kita pada waktu-waktu yang demikian,untuk menimbulkan penghargaan kita kepada hasil keamanan yang kita capai dengan membayar mahal. Karena pak Soekarno pun pernah menyebutkan bahwa “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya”.
Penting sekali buku ini, untuk kita kenang kembali bagaimana suasana, kondisi dan situasi tanah air kita pada waktu-waktu yang demikian,untuk menimbulkan penghargaan kita kepada hasil keamanan yang kita capai dengan membayar mahal. Karena pak Soekarno pun pernah menyebutkan bahwa “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya”.
Selain novel,saya juga menemukan hal yang menarik dari judul Kota Palopo Yang
Terbakar ini. Saya menemukan sebuah lagu yang berjudulkan sama. Saya kutipkan
sedikit dalam resensi ini.
Kota Palopo yang terbakar,
terbakar oleh api.
Kiri kanan api menyala
sedang dipandang hati nan susah.
Tengok kekiri ke Salobulo,
tengok kekanan gunung Pattene,
tengok kemuka ada satu pulau yang kecil,
nama pulau Libukang.
Hai Penggoli Batupasi,
tambah lagi Pongjalae...
Kota Palopo yang terbakar,
terbakar oleh api.
Kiri kanan api menyala
sedang dipandang hati nan susah.
Tengok kekiri ke Salobulo,
tengok kekanan gunung Pattene,
tengok kemuka ada satu pulau yang kecil,
nama pulau Libukang.
Hai Penggoli Batupasi,
tambah lagi Pongjalae...
e e e...... lupa sudah.
Sumber:
http://profesorbodoh.blogspot.com/2010/08/resensi-novel.html